Jokowi Pasca Lengser: 'Resah Yang Menjelma Kegelisahan'
Oleh: Ali Syarief
Akademisi
Di Indonesia, masa purnatugas presiden biasanya menjadi masa redup. Megawati Soekarnoputri mengunci diri dalam keheningan partai.
Susilo Bambang Yudhoyono, dengan gaya elegan, membangun Cikeas sebagai semacam think tank dan rumah konsolidasi politik.
Bahkan B.J. Habibie yang sebentar menjabat, menghabiskan masa senjanya dengan laboratorium riset, yayasan pendidikan, dan cita-cita ilmu pengetahuan.
Namun, Joko Widodo tampaknya menolak pola itu. Setelah lengser dari Istana, ia justru makin sering terlihat di layar kaca, media sosial, dan ruang-ruang politik informal.
Ia hadir di mana-mana: meninjau ke daerah-daerah membuka pertemuan bisnis, berkeliling sawah, bahkan muncul dalam manuver-manuver kekuasaan yang seolah tak pernah benar-benar ditinggalkannya.
Jokowi seperti mengalami fase hyperactivity post-power syndrome—suatu kegelisahan laten pasca-kekuasaan yang mencari-cari pelampiasan.
Apa Yang dikejar?
Tak seperti Megawati yang punya PDI Perjuangan sebagai “mainan abadi”, atau SBY yang menenangkan diri dalam Partai Demokrat dan karya-karya seni lukisnya, Jokowi terlihat tak punya kanal pelepasan yang berjangkar ideologis maupun kultural.
Ia tidak membangun yayasan pendidikan ala Habibie, tidak menyuarakan gagasan lingkungan, tidak membentuk pusat kebudayaan, bahkan tak terdengar ingin mendirikan perpustakaan pribadi sebagaimana dilakukan oleh pemimpin-pemimpin besar dunia pascarezim.
Sebaliknya, ia justru terlihat seperti sedang menyelamatkan sesuatu. Atau seseorang.
Yakni dirinya sendiri, keluarganya, dinasti kecil yang lahir dari ambisinya mempertahankan kekuasaan melampaui mandat konstitusional.





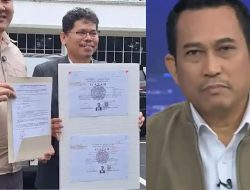





Artikel Terkait
Ijazah Jokowi Akhirnya Terbuka: Apa yang Ditemukan KPU dan Mengapa Bonatua Masih Penasaran?
Isi Surat Rahasia Ammar Zoni ke Prabowo: Grasi atau Rehabilitasi?
Hyundai Targetkan Jual 2000+ Unit di IIMS 2026, Ini Model Andalan untuk Mudik Lebaran
Target Gila Hyundai di IIMS 2026: Serbu 2000+ Unit dengan Strategi Ramadan & Mobil Mudik Terlengkap!