Kemerdekaan bagi sebuah bangsa dan negara bukan sebatas perjuangan untuk bebas dari penjajah, tetapi kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemandirian, kedaulatan, keberpijakan, keteguhan, prinsip dasar, serta identitas bagi suatu bangsa untuk berdiri di kakinya sendiri tanpa tekanan dan pegaruh dari bangsa lain. Dan konsep kemerdekaan tidak sebatas “pembebasan” tetapi kemerdekaan senantiasa bersinggungan dengan nasionalisme sebuah bangsa. Nasionalisme dipandang sebagai akar kekuatan budaya senasib sepenanggungan—dengan semangat inilah yang kemudian membentuk konsensus politik bagi suatu bangsa untuk mencapai cita-cita kemerdekaan.
Secara terminologis kata nasionalisme berasal dari kata nationalism atau nation dalam bahasa Inggris. Dalam penelitian kemaknaan, kata nation berasal dari kata dalam bahasa Latin, yaitu natio, yang berakar dari kata nascor yang berarti 'aku lahir', atau dari kata natus sum, yang berarti 'aku dilahirkan'. Dalam perkembangan maknanya kata nation merujuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara dalam mencintai tanah air dan bangsanya di mana mereka bertempat tinggal.
Negara-negara yang pernah berada dalam koloni sebagai negara jajahan, pada prinsipnya mereka berjuang dengan semangat nasionalisme, ras, agama, budaya, dan nilai-nilai luhur—untuk melawan kolonialisme penajajah. Indonesia, dalam hal ini memiliki sejarah panjang untuk membangun nasionalisme demi cita-cita kemerdekaan. Jauh sebelum itu, kolonialisme di Indonesia telah berhasil membentuk primordialisme lokal, yang memudahkan kaum penjajah untuk menguasai bukan hanya sumber daya alam, tetapi juga menguasai sekaligus merampas hak-hak individu manusia Indonesia. Keterbelengguan ini menyebabkan interdependensi yang kuat, sehingga di era itu tidak mengherankan keterpecahan di tubuh masyarakat (rakyat) terlihat dengan jelas. Ada yang memilih jadi budak (penghianat) hanya demi uang dan kekuasaan. Tuan-tuan tanah diberikan privelege oleh penjajah sebagai politik devide et impera (politik adu domba).
Kesadaran akan nasionalisme bagi Indonesia dimulai sejak lahirnya Budi Utomo tahun 1908 dengan cita-cita kemerdekaan. Kolonialisme merupakan bara yang membakar semangat nasionalisme bangsa Indonesia untuk melepaskan keter-jajahan dari Jepang, Belanda dan sekutunya. Nasionalisme menjadi senjata yang ampuh untuk menghardik penajajah dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan tujuan untuk meneguhkan prinsip-prinsip kedaulatan sebagai negara yang merdeka. Bagaimana Soekarno, Jenderal Soedriman, dan Bung Tomo harus menghadap KH. Hasyim Asy’ari hanya untuk meminta fatwa; apa hukumnya nasionalisme dalam upaya membela bangsa, negara dan tanah air. Dan KH. Hasyim Asy;ari selalu memberikan jawaban setelah sholat qiyamul lail. Artinya, bahwa nasionalisme bukan sebatas semangat primordialisme, namun Islam lewat tokoh ulamanya telah memberikan jalan bagi perjuangan dan kemerdekaan bagi Indonesia.
Nasionalisme Merebut kedaulatan
Pikiran tentang kedaulatan dimulai pada akhir abad ke-18, khususnya dengan Revolusi Prancis dan penyebaran prinsip kedaulatan rakyat atau penentuan nasib sendiri, gagasan bahwa "rakyat" harus berkuasa dikembangkan oleh para ahli teori politik. Tiga teori utama telah digunakan untuk menjelaskan munculnya nasionalisme: Pertama, Primordialisme berkembang bersamaan dengan nasionalisme selama era Romantis dan berpendapat bahwa selalu ada bangsa. Pandangan ini telah ditolak oleh sebagian besar cendekiawan, yang memandang bangsa sebagai sesuatu yang dibangun secara sosial dan bergantung pada sejarah. Perennialisme, versi primordialisme yang lebih lunak yang menerima bahwa bangsa adalah fenomena modern tetapi memiliki akar sejarah yang panjang, menjadi bahan perdebatan akademis.
Kedua, Teori modernisasi, yang saat ini merupakan teori nasionalisme yang paling umum diterima, mengadopsi pendekatan konstruktivis dan mengusulkan bahwa nasionalisme muncul karena proses modernisasi, seperti industrialisasi, urbanisasi, dan pendidikan massal, yang memungkinkan kesadaran nasional. Para pendukung teori ini menggambarkan bangsa sebagai "komunitas yang dibayangkan" dan nasionalisme sebagai "tradisi yang diciptakan" di mana sentimen bersama memberikan bentuk identitas kolektif dan mengikat individu bersama dalam solidaritas politik. Ketiga, Etnosimbolisme menjelaskan nasionalisme sebagai produk simbol, mitos, dan tradisi, dan dikaitkan dengan karya Anthony D. Smith.
Moral value atas nasionalisme, yakni bagaimana melihat relasi antara nasionalisme dan patriotisme, dan kesesuaian nasionalisme dan kosmopolitanisme semuanya merupakan subjek perdebatan filosofis. Nasionalisme dapat dipadukan dengan berbagai tujuan dan ideologi politik seperti konservatisme (konservatisme nasional dan populisme sayap kanan) atau sosialisme (nasionalisme sayap kiri).
Dalam praktiknya, nasionalisme dipandang positif atau negatif tergantung pada ideologi dan hasilnya. Nasionalisme telah menjadi ciri gerakan untuk kebebasan dan keadilan, telah dikaitkan dengan kebangkitan budaya, dan mendorong kebanggaan atas pencapaian nasional. Nasionalisme juga telah digunakan untuk melegitimasi perpecahan rasial, etnis, dan agama, menekan atau menyerang kaum minoritas, melemahkan hak asasi manusia, pelemahan dalam tradisi demokrasi, dan terjadinya konflik dan perang. Egosentrisme primordialis di beberapa negara seringkali memicu terjadinya konflik dan peperangan antar geng, suku dan antarbangsa.
Karena itu pentingnya memahami nasionalisme sebagai sebuah paradigma dalam bernegara. Pertama, Nasionalisme kewarganegaraan (atau nasionalisme sipil) adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh legitimasi politik dari peran aktif rakyatnya, "kehendak rakyat"; "perwakilan politik rakyat". Teori ini mula-mula dikembangkan oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi rujukan dalam berbagai bidang ilmu sosial dan politik. Sebagaimana salah satu karyanya yang terkenal yakni “Du Contract Sociale” atau dikenal dengan istilah “Teori Kontrak Sosial” bahwa negara atau kekuasaan keterwakilan politik rakyat menjadi penting—untuk membangun check and balances yang berakar dari kontrak sosial dalam proses berpolitik.
Kedua, Nasionalisme etnis adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh legitimasi dan dukungan politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Pandangan ini pertama kali diperkenalkan oleh Johann Gottfried von Herder, yang memperkenalkan konsep Volk (bahasa Jerman untuk "rakyat"). Dalam pandangan Gabriel A. Almond dalam bukunya “The Political Culture” menyebutkan bahwa dalam politik budaya, etnis, adat istiadat dalam masyarakat seringkali menjadi kekuatan di dalam memberi dukungan politik (legitimasi politik) Gabriel menyebutnya dengan istilah patron klien.
Ketiga, nasionalisme romantik (juga disebut nasionalisme organik, nasionalisme identitas) adalah lanjutan dari nasionalisme etnis di mana negara memperoleh legitimasi politik secara semulajadi ("organik") hasil dari bangsa atau ras; menurut semangat romantisme. Nasionalisme romantik adalah bergantung kepada perwujudan budaya etnis yang menepati idealisme romantik; kisah tradisi yang telah direka untuk konsep nasionalisme romantik. Misalnya "Grimm Bersaudara" yang dinukilkan oleh Herder merupakan koleksi kisah-kisah yang berkaitan dengan etnis Jerman dalam politik saat itu.
Sedangkan yang keempat, nasionalisme Budaya adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh legacy politik dari budaya bersama, dan bukan diperoleh melalui struktur keturunan.ras dan warna kulit. Contoh yang terbaik ialah rakyat Tionghoa yang menganggap negara adalah berdasarkan kepada budaya. Unsur ras telah dikesampingkan, di mana golongan Manchu serta ras-ras minoritas lain masih dianggap sebagai rakyat negara Tiongkok. Kesediaan dinasti Qing untuk menggunakan adat istiadat Tionghoa membuktikan keutuhan budaya Tionghoa. Malah banyak rakyat Taiwan menganggap diri mereka nasionalis Tiongkok sebab persamaan budaya mereka tetapi menolak RRT karena pemerintahan RRT berpaham komunisme.
Kelima, nasionalisme kenegaraan ialah variasi nasionalisme kewarganegaraan, selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik adalah kuat sehingga diberi lebih keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Hal ini daopat kita saksikan dalam Nazisme, serta nasionalisme Turki kontemporer, dan dalam bentuk yang lebih kecil, Franquisme sayap-kanan di Spanyol, serta sikap 'Jacobin' terhadap unitaris dan golongan pemusat negeri Prancis, seperti juga nasionalisme masyarakat Belgia, yang secara ganas menentang demi mewujudkan hak kesetaraan (equal rights) dan lebih otonomi untuk golongan Fleming, dan nasionalis Basque atau Korsika.
Bahwa nasionalisme yang sempit dalam kondisi bernegara akan memberikan dua dampak sekaligus; (1) Nasionalisme atas kebangsaan dengan konsep senasib sepenanggungan, akan memberi spirit perlawanan atas penindasan, penajajahan dan ketidak-bebasan negara karena adanya domnasi negara lain. Nasionalisme kemudian akan memunculkan move politik—dengan agenda pembebasan bangsa dan tanah air untuk mewujudkan kedaulatan dalam negara. (2) Nasionalisme sempit, seperti egosentrisme lokal, primordialisme, etnis, budaya, ras dan warna kulit, agama—dengan cara pengkultusan dan pen-taklikan secara membabi buta, cendrung akan memicu konflik dan bahkan perang sekalipun.
Musuh negara di era modern
Indonesia dalam rentang sejarah yang demikian panjang, lapis-lapis kebangsaan dan kebudayaan serta pergolakan yang menjadi dinamikanya yang terus berkembang hingga detik ini. Fase kepemimpinan politik berganti setiap lima tahunan melalui proses Pemilu. Dinamika politiknya pun akan berbeda. Usia kemerdekaan Indonesia yang menginjak 80 tahun—bukan tidak mungkin tantangan itu tidak sedikit.
Kemiskinan ekstrem, angka pengangguran yang tinggi, sulitnya lapangan kerja, angka PHK yang tinggi, korupsi yang semakin menggila, kenaikan pajak PBB di luar batas, gaji dan tunjangan elit kekuasaan yang semakin kehilangan sense of crisis, tagihan royalty musik—semua ini adalah model kolonialisme baru (New Colonialism), sementara di penjuru republik ini masih ada anak-anak yang tidak dapat sekolah karena tidak punya akses dan biaya, masih ada seorang bidan desa yang harus menyeberang sungai hanya untuk membantu ibu hamil yang mau melahirkan, di kampung-kampung tidak sedikit anak-anak yang menahan lapar, menahan sakit, karena mereka tidak punya uang untuk beli beras dan obat. Sementara kekuasaan sedang sibuk membagi-bagi jabatan komisaris di BUMN, menaikan gaji anggota DPR 3 juta perhari. Menaikkan gaji hakim, walau tidak ada jaminan hukum akan tegak dengan prinsip-prinsip keadilan. Ada yang tidak terbukti bersalah namun dikerangkeng dalam tahanan, ada yang sudah incrah dan dinyatakan bersalah tetapi tetap dibiarkan berkeliaran tanpa tersentuh hukum. Dan inilah sisi gelap dalam penegakan hukum di republik ini.
Sekedar mengingat pernyataan presiden pertama RI Soekarno “Musuh, penjajah telah kita usir dari bangsa ini, kedepan musuhmu adalah bangsamu sendiri”. Pernyataan Soekarno terasa saat-saat ini—seperti kriminalisasi hukum terhadap beberapa aktivis adalah contoh kecil perlakuan negara (kekuasaan) terhadap rakyatnya. Pajak yang dilegitimasi atas nama negara memalak rakyatnya alih-alih demi pembangunan.
Sehingga dengan demikian Korupsi dan supremasi hukum (Law Supremation) harus menjadi musuh bersama (common enemy), sebab kalau korupsi tidak dicegah dengan kekuatan hukum maka (bisa jadi) pemerintahan akan kehilangan kepercayaan dari publik (Distrust public)—dan kalau distrust publik meluas, pada akhirnya akan memunculkan delegitimasi politik. Tentu ini akan berbahaya bagi keberkangsungan pemerintahan bila publik sudah manaruh anlegacy terhadap kekuasaan yang sah.
Termasuk supremai hukum yang masih sangat amburadul dapat memicu beberapa hal diantaranya; Pertama, sulitnya investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena ketakutan tidak memnadapatkan kepastian hukum (Accidenty). Kedua, lemahnya penegakan hukum akan memicu gesekan sosial, karena keberpihakan penegak hukum bukan pada prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Dua hal ini berkecendrungan akan berdampak pada pendelegitiamsian pada hukum negara, sehingga berpotensi memunculkan “Homo Homini Lupus” yang dianggap benar oleh rakyat.
Perilaku korupsi, dan penegakan hukum masih timpang (Das sein und Das Sollen)—Julia Kristeva (seorang teoritikus, ahli linguistik, kritikkus sastra, psikoanalis dan novelis—berdarah Bulgaria), menulis buku yang berjudul “Bangsa Tanpa Nasionalisme”, sekalipun karya ini mengkritik bangsa-bangsa Eropa, dengan meihat faktor terjadinya krisis identitas dalam relasi berbangsa, konflik dan perecahan terjadi di mana-mana. Namun dari karya tersebut, kita berani melihat kondisi Indonesia hingga saat ini—bahwa korupsi yang menggila, penegakan hukum yang amburadul menjadi tesis kalau kita sebagai bangsa Indonesia mengamini apa yang ditulis Julia Krsiteva tentang “bangsa Tanpa Nasionalisme”. Sekali lagi, nasionalisme itu wujud kecintaan terhadap bangsa, bukan dengan cara merampoknya dengan perilaku korupsi, dan merusaknya dengan perialku penegakan hukum yang amburadul.
Oleh sebab itu, di usia kemerdekaan yang sudah memasuki usia yang cukup tua (80 tahun) ini—tantangannya juga demikian kompleks. Pemimpin butuh tangan besi untuk membangun pemerintahan yang bersih dari parktek korupsi yang merugikan negara menjadi pemerintahan yang bersih dari KKN (Good Governance dan clean Governance sebagaimana amanat reformasi tahun 1998. Nasionalisme berbangsa harus menjadi instrumen penting untuk mewujudkan kedaulatan. Kedaulatan tak semata pengakuan dari negara-negara lain, tetapi kedaulatan yang substantif adalah berpegang teguh pada prinsip-prinsip kemerdekaan, dan disegani oleh bangsa-bangsa lain.
Dengan harapan semoga presiden Prabowo Subianto bisa melakukan itu demi kepentingan rakyat, dan kemajuan bangsa di masa-masa mendatang.
Oleh: Saifuddin
Direktur Eksekutif LKiS
Dosen, Peneliti, Penulis buku, kritikus sosial politik, penggiat demokrasi.
______________________________________
Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan POLHUKAM.ID terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi POLHUKAM.ID akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.


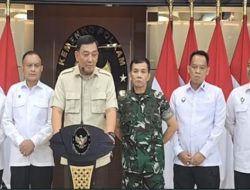



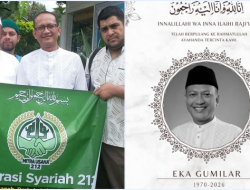


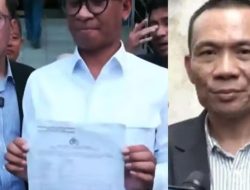

Artikel Terkait
Eggi Sudjana Ungkap Isi Dialog Rahasia dengan Jokowi: Kita Sama-Sama Sakit
Innalillahi! Eka Gumilar, Tokoh Kunci Rekat Indonesia dan GRIB Jaya, Meninggal Dunia: Apa Dampaknya?
Jokowi Bantah Keras Jadi Wantimpres Prabowo, Ini Alasan Nyata Pilih Tetap di Solo
Gus Ipul Bantah Keras Wali Kota Denpasar: Penonaktifan BPJS Bukan Perintah Presiden!