Keterbukaan dalam politik bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu masuk menuju pertanggungjawaban.
Publik tidak hanya membutuhkan ruang untuk bicara, tetapi juga keadilan atas kebijakan yang menyimpang.
Jokowi harus dipanggil ke ruang pengadilan moral, bahkan konstitusional, untuk menjawab jejak kesalahan yang ditinggalkan.
Demikian pula dengan Gibran. Kehadirannya sebagai wakil presiden dianggap sebagai produk manipulasi politik dan penyalahgunaan hukum konstitusi.
Jika sistem benar-benar mulai berani membuka diri, maka langkah berikutnya tak terhindarkan: proses pemakzulan harus dipertimbangkan sebagai koreksi sejarah.
Keniscayaan yang Tak Bisa Ditawar
Ada pepatah politik: “sekali pintu dibuka, udara bebas akan masuk dengan deras.” Begitu pula dalam konteks ini.
Begitu legislatif dan eksekutif membuka diri terhadap aspirasi mahasiswa dan rakyat, gelombang kritik akan semakin tak terbendung. Dari wacana transparansi, akan lahir desakan akuntabilitas.
Dari akuntabilitas, akan tumbuh tuntutan pertanggungjawaban. Dan pada akhirnya, pertanggungjawaban itu bermuara pada dua kata tegas: adili Jokowi, makzulkan Gibran.
Kesadaran ini bukan sekadar retorika politik, melainkan keniscayaan sejarah. Demokrasi yang terciderai selama satu dekade terakhir menuntut pemulihan.
Dan pemulihan itu tak bisa hanya dilakukan dengan dialog kosong, melainkan melalui keberanian menegakkan keadilan pada penguasa yang menyalahgunakan amanah rakyat.
Sumber: FusilatNews




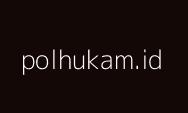



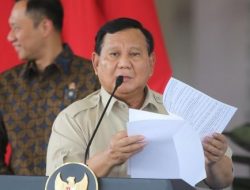


Artikel Terkait
Bukan Dibangun Pakai Uang Rakyat! Ini Fakta Mengejutkan di Balik Masjid Jokowi di Abu Dhabi
Bayar Utang Whoosh dengan Uang Koruptor? Ini Rencana Kontroversial Prabowo
Maxim Indonesia: Rahasia Pesan & Daftar Driver untuk Hasilkan Cuan!
Prabowo Gaspol! Whoosh Tak Cuma ke Surabaya, Tapi Diteruskan Sampai Ujung Jawa Timur